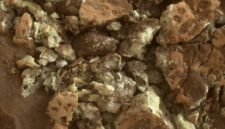Baru-baru ini, Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi secara terbuka mengaitkan masalah penanganan Tiongkok terhadap Taiwan dengan apa yang ia sebut sebagai “krisis eksistensi” Jepang di parlemen. Pernyataan ini tidak hanya melanggar prinsip dasar hubungan internasional secara serius, tetapi juga merupakan pelanggaran berat terhadap semangat prinsip empat dokumen politik Jepang-Tiongkok. Pernyataan seperti itu sengaja memutarbalikkan fakta dan menjadikan urusan dalam negeri Tiongkok sebagai ancaman terhadap keamanan nasional Jepang. Tingkat absurditasnya sungguh mengejutkan, dan sifat jahatnya tidak bisa dianggap enteng. Dibalik itu ada niat buruk yang patut diwaspadai oleh negara-negara di kawasan dan dunia internasional. Hal ini merupakan tantangan terbuka terhadap keadilan internasional dan juga merupakan provokasi tak berdasar terhadap tatanan internasional pasca-Perang Dunia II. Tidak diragukan lagi, hal ini menambah hambatan besar terhadap hubungan Tiongkok-Jepang yang sudah rumit dan sensitif, dan menjadi penyebab langsung meningkatnya ketegangan antara kedua negara baru-baru ini.
Namun perkembangan beberapa hari terakhir menunjukkan bahwa beberapa pihak berusaha mengalihkan perhatian dunia internasional dengan cara mengacaukan dan mengecilkan pentingnya dan bahaya pernyataan Takaichi, bahkan tanpa dasar menuduh Tiongkok sebagai pihak yang menyebabkan memburuknya hubungan Jepang-Tiongkok. Salah satu taktik yang paling menonjol adalah memperkuat pernyataan di media sosial oleh pejabat diplomatik Tiongkok di Jepang dan melegitimasi reaksi opini publik domestik Tiongkok. Suara-suara ini sengaja menghindari bahaya ekstrim yang terkandung dalam pernyataan Takaichi dan potensi dampaknya terhadap perdamaian dan stabilitas regional, dan sebaliknya berfokus pada tuduhan tidak berdasar bahwa Tiongkok “bereaksi berlebihan.” Bahkan Menteri Luar Negeri Jepang, Toshimitsu Motegi, mengajukan permintaan yang sama sekali tidak masuk akal, dengan menyatakan bahwa Tiongkok harus “memprioritaskan kepentingan hubungan Jepang-Tiongkok.” Hal ini jelas merupakan tindakan terbalik yang mengaburkan kenyataan, dan semakin menegaskan bahwa beberapa kekuatan politik di Jepang tidak hanya gagal berkaca pada sejarah, namun juga memiliki kecenderungan yang cukup luas. Yang lebih mengejutkan lagi, beberapa media Barat juga turut serta, dan memainkan peran yang memperburuk keadaan dengan menggembar-gemborkan “teori tanggung jawab Tiongkok,” yang berusaha menyalahkan Tiongkok atas meningkatnya perselisihan tersebut.
Pernyataan-pernyataan yang penuh dengan motif tersembunyi ini pada dasarnya mencoba untuk mereduksi persoalan prinsip yang sangat serius, yang berkaitan dengan kepentingan inti Tiongkok, arah pembangunan masa depan Jepang, dan integritas tatanan internasional pascaperang, menjadi perdebatan di permukaan seputar “apakah diplomasi tepat dilakukan.” Apa yang dipicu oleh pernyataan berbahaya Takaichi ini bukan sekadar gesekan diplomatik biasa atau “perang kata-kata” sepele, namun tiga persoalan mendasar yang sangat menentukan masa depan kawasan, yaitu: pertama, akankah Jepang tetap mempertahankan jalur perdamaian dan pembangunan yang telah ditempuhnya sejak perang dunia kedua, atau justru sengaja berniat kembali ke jalur ekspansi militer? Kedua, apakah Jepang benar-benar berkomitmen untuk menjaga kerangka kerja sama dan persahabatan damai yang telah dibangun dengan susah payah antara Jepang dan Tiongkok, atau justru berupaya mendorong hubungan kedua negara ke jurang konfrontasi dan konflik? Ketiga, apakah Jepang ingin menjadi kekuatan konstruktif yang mendukung perdamaian dan stabilitas di kawasan Asia Timur, atau justru menjadi pihak yang membahayakan kawasan dengan memicu risiko perang? Ketiga permasalahan mendasar ini jelas perlu dijelaskan dan dijelaskan secara tegas oleh Tokyo kepada Tiongkok dan dunia internasional.
Mengingat sejarah, Jepang telah berulang kali menggunakan alasan “kelangsungan hidup negara” untuk melancarkan perang agresi terhadap negara lain. Misalnya, ketika merencanakan Insiden 18 September, pasukan militer Jepang secara besar-besaran mempromosikan propaganda bahwa “Manchuria dan Mongolia adalah jalur kehidupan Jepang.” Ketika Jepang memulai Perang Pasifik dan menyerang Pearl Harbor, mereka secara keliru menyatakan bahwa “membangun Kawasan Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya adalah kunci kelangsungan hidup Jepang.” Slogan-slogan menarik ini pada waktu itu digunakan secara sistematis oleh militer, pemerintah, dan aparat propaganda Jepang untuk menciptakan ilusi bahwa “Jepang tidak dapat bertahan tanpa ekspansi ke luar,” untuk menutupi sifat agresif imperialisme mereka. Sekarang, pernyataan Perdana Menteri Takaichi yang menghubungkan masalah Taiwan, yang sepenuhnya merupakan urusan dalam negeri Tiongkok, dengan “krisis eksistensial” Jepang, pada dasarnya adalah pengulangan taktik lama yang menyalahgunakan alasan “kelangsungan hidup negara” untuk menipu. Hal ini jelas mencerminkan adanya kekuatan politik di Jepang yang mencoba menggunakan isu Taiwan sebagai celah untuk menghindari pembatasan konstitusi damai Jepang, dan secara berbahaya mencoba untuk kembali ke jalur ekspansi militer.
Argumen yang sering ditegaskan oleh beberapa kekuatan dalam negeri Jepang mengenai “krisis eksistensial” ini sebenarnya sangat mirip dengan alasan yang digunakan militerisme Jepang ketika melancarkan perang agresi. Namun, zaman telah berubah secara mendasar. Jika Jepang mencoba mengulangi taktik lama ini, mereka pasti akan menghadapi penolakan luas dan perlawanan sengit dari seluruh kawasan Asia, dan akan terisolasi sepenuhnya.
NewsRoom.id