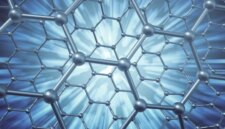0oleh: Rosadi Jamani
MESKIPUN Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) sudah meminta bantuan internasional, Presiden Prabowo Subianto bergeming. Ia tetap bersikukuh tak ingin statusnya menjadi bencana nasional.
Prabowo menyatakan situasi terkendali. Ini “hanya” tiga provinsi dari 38 provinsi dan Indonesia “mampu” tanpa status bencana nasional.
Pernyataan tersebut secara langsung berbanding terbalik dengan kenyataan tidak ikut serta dalam rapat kabinet. Pasalnya, tiga provinsi yang disebut “masih terkendali”, hingga 16 Desember 2025, menurut data resmi BNPB, sudah memakan korban jiwa sebanyak 1.030 orang.
Aceh menyumbang duka terdalam dengan 431 orang meninggal, disusul Sumatera Utara 355 orang, dan Sumatera Barat 244 orang.
Cerita belum selesai, sebab 206 orang masih dinyatakan hilang, tergantung antara harapan keluarga dan kemungkinan terburuk.
Pada titik inilah kata “dikendalikan” mulai terdengar seperti istilah teknis yang kehilangan cita rasa.
Sebab selain korban jiwa, tercatat sekitar 7.000 orang luka-luka, lebih dari 624.000 orang mengungsi, dan 186.488 rumah rusak – angka yang cukup untuk membangun kota baru, jika kota tersebut tidak dibangun dari puing-puing dan trauma.
Negara memobilisasi sumber daya, namun landasan pelayanan publik juga runtuh. Terdapat 219 fasilitas kesehatan yang terdampak, ironisnya di saat warga paling membutuhkan pengobatan. Terdapat 967 fasilitas pendidikan yang rusak sehingga anak-anak belajar langsung dari silabus bencana.
Ada 434 tempat ibadah yang terdampak, sehingga salat pun harus antri. Selain itu, 290 gedung perkantoran dan 145 jembatan ambruk, tidak hanya memutus akses jalan, tetapi juga ritme kehidupan masyarakat.
Di tengah-tengah angka-angka inilah muncul suatu kontras yang sulit untuk ditutupi. Ketika pusat berbicara mengenai kemandirian nasional dan menolak bantuan luar demi harkat dan martabat negara, Gubernur Aceh justru terang-terangan meminta bantuan internasional, menulis kepada UNDP dan UNICEF, dua badan PBB yang bagi Aceh bukan sekedar nama, melainkan penyelamat yang hadir nyata pasca tsunami tahun 2004.
Permintaan tersebut bukan drama politik, melainkan refleksi di lapangan. Infrastruktur hancur, pengungsi menumpuk, logistik dan layanan dasar kewalahan.
Bahkan bantuan dari Malaysia dan China sudah mulai berdatangan, sementara relawan internasional bersiap turun.
Jadi di sinilah kedua narasi tersebut saling berhadapan. Dari Jakarta terdengar suaranya, kita bisa melakukannya sendiri.
Dari Aceh ada gaung, kami butuh bantuan. Yang satu berbicara tentang kapasitas negara, yang satu lagi berbicara tentang ketahanan masyarakat. Keduanya benar, namun tingkat penderitaannya tidak sama.
“Tidak menyatakan status bencana nasional” mungkin sah secara administratif, mungkin juga strategis secara politik.
Namun data BNPB menunjukkan satu hal, kemampuan negara untuk menolak bantuan eksternal tidak secara otomatis berarti bahwa penderitaan di lapangan telah teratasi.
Kemerdekaan nasional diuji bukan oleh dunia internasional, melainkan oleh 1.030 nyawa yang hilang, 206 orang yang belum ditemukan, dan ratusan ribu warga yang masih hidup sebagai pengungsi hingga saat ini.
Nah, ketika kita mendengar kata “dikendalikan”, pertanyaannya sederhana saja, dikendalikan menurut siapa? Menurut meja rapat, atau menurut lumpur yang masih setinggi dada di desa Aceh, Sumut, dan Sumbar?
“Biasanya seminggu setelah banjir surut, rumah-rumah sudah bisa ditempati lagi. Nah ini banjir lumpur setinggi dada, bahkan ada yang tenggelam di lumpur. Tidak bisa lagi ditempati,” teriak pengungsi Aceh.
Pada akhirnya, perdebatan ini bukan soal siapa yang paling nasionalis atau siapa yang paling percaya diri untuk berdiri sendiri.
Ini masalah waktu, nyawa, dan skala cederanya. Data BNPB tidak memberikan opini, 1.030 orang meninggal, 206 orang hilang, 624.000 lebih mengungsi, 186.488 rumah rusak, ratusan fasilitas umum lumpuh.
Tokoh-tokoh ini tidak kenal pidato, tidak peduli dengan jargon kemerdekaan, dan tidak tunduk pada status administratif. Dia hanya mencatat siapa yang selamat dan siapa yang tidak.
Jadi kemerdekaan sejati tidak diukur dari seberapa tegas mereka menolak bantuan dunia, namun dari seberapa cepat suatu negara memastikan bahwa warganya tidak dibiarkan sendirian terlalu lama.
Jika pusat mengatakan “kita bisa melakukannya sendiri”, sementara daerah seperti Aceh terpaksa membuka pintu internasional untuk menyelamatkan rakyatnya, maka yang perlu didamaikan bukanlah semangatnya, melainkan kenyataan.
Karena negara besar bukanlah negara yang malu untuk ditolong, dan juga bukan negara yang berani naik podium namun lamban dalam lumpur. Negara yang besar adalah negara yang berani berkata: kita kuat, kita bekerja, dan kalau perlu, demi kehidupan umat manusia, kita tidak bangga menerima uluran tangan.
Di situlah letak martabat yang sebenarnya, bukan pada penolakan, melainkan pada pihak yang paling cepat mencapai korbannya.
Tutup buku. Matikan mikrofon. Keluar ke lapangan. Sebab di sana, di tengah air keruh dan rumah yang hilang, satu pertanyaan terus menghantui, bukan lagi apakah negara ini mampu berdiri sendiri, tapi apakah negara ini cukup cepat menghadapi mereka yang harapannya sudah hampir pupus.
(Ketua Satupena Kalimantan Barat)
NewsRoom.id